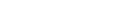Eksklusivisme, Inklusivisme, Pluralisme, dan Dialog Antar Agama
Abstract
... cukup banyak gereja atau sinode di zaman pascamodern ini yang mengutamakan pentingnya relasi antar-agama atau antar-iman. Mereka agaknya tidak mementingkan apa ajaran yang dipegang seseorang, sebuah lembaga, atau sebuah aliran. Memang, mau tidak mau pada masa kini kita hidup di dalam dunia yang secara religius bersifat plural atau majemuk, dan kebanyakan orang akan setuju bila dikatakan bahwa kekristenan pun, siap atau tidak, dipandang hanyalah sebagai salah satu agama dunia di antara agama-agama lainnya. Teolog modern atau pascamodern pada umumnya memilih posisi “aman” dan dapat diterima semua pihak, yaitu bahwa setiap agama memiliki warisan historis dan jalan keselamatannya sendiri-sendiri.3 Secara khusus, di Indonesia, kita hidup di tengah beragamnya suku, ras, tradisi, latar belakang sosial dan agama. Bagi kekristenan, pluralitas budaya dan agama ini dapat memperlihatkan aspek-aspek positif maupun negatif. Dari perspektif positif, kita harus mengakui bahwa pluralitas kepercayaan dapat memperkaya dan sekaligus menantang pemahaman Kristen secara lebih perseptif dan realistis tentang keberagaman ini; hasilnya, pelayanan Kristen akan jadi lebih relevan dan kontekstual bagi kebutuhan manusia. Dari perspektif negatif, kita juga harus mengakui bahwa pluralitas kepercayaan ini dalam keadaan-keadaan tertentu telah menjadi penyebab timbulnya ketegangan dan konflik-konflik di antara keyakinan-keyakinan tersebut. Lalu, bagaimana seharusnya orang Kristen mendekati topik pluralisme? Melalui artikel ini saya pertama-tama akan menguji fakta pluralisme dalam dunia kita saat ini. Kita akan mengamati pluralisme sosiokultural modern dan dampaknya terhadap teologi Kristen. Kemudian kita akan menyelidiki bagaimana pluralisme telah dimanfaatkan untuk membenarkan agenda teologis belakangan ini yang dikenal sebagai “teologi agama-agama dunia” atau “teologi pluralistik.” Di sini tampaknya, oleh mereka, iman Kristen harus diletakkan sebagai dikotomi atau alternatif antara partikularisme dan inklusivisme. Yang pertama berarti orang Kristen sebaiknya tidak menyajikan iman mereka dengan cara sedemikian rupa seakan-akan mereka adalah “mayoritas,” “pemimpin,” “anak tunggal yang terkasih” di antara agama-agama lainnya. Yang belakangan berarti orang Kristen seharusnya mengadakan atau ikut serta dalam dialog dengan anggota iman atau agama lain sehingga kekristenan itu sendiri dapat diperkaya, atau bahkan diubahkan melalui interaksi serta menyerap kebenarankebenaran yang terdapat dalam tradisi lain. Itu sebabnya sebelum kita tiba pada implikasi di bagian akhir, saya akan mengajukan sebuah kerangka alternatif sebagai suatu usaha untuk melangkah melampaui kontroversi, yakni mengajukan sebuah kerangka yang bisa dikerjakan di mana perbedaanperbedaan pemikiran adalah sah dan tidak direlatifkan atau diabsolutkan.